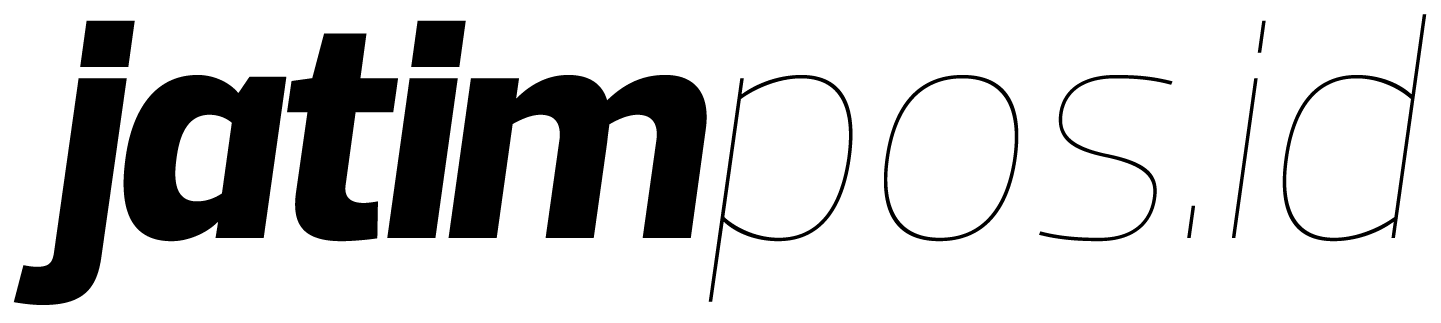Rocky Gerung, Filsafat dan Elektabilitas
 PegiaT Filsafat, Rocky Gerung/Foto: DPP PKS.
PegiaT Filsafat, Rocky Gerung/Foto: DPP PKS.
Entah kebetulan atau disengaja, beberapa hari belakangan barisan figur “ternama” ramai-ramai mengkritik posisi politik Rocky Gerung (RG) yang doyan mengkritik Presiden. Tak kurang dari Ketua DPD Golkar DKI, Rizal Mallarangeng, pemilik tukang survei, Denny JA, Lembaga Studi Filsafat Nahdliyyin (LSFN), skolar-skolar Filsafat, dan seterusnya, turut ambil bagian dalam barisan tersebut.
Tak hanya itu, dua Seminar Filsafat diadakan di Jakarta & Malang dalam waktu berselang tak terlalu lama, menghadirkan para pembicara kunci yang dianggap memiliki otoritas untuk berbicara Filsafat. Melalui symptomatic reading, dua seminar itu secara samar-samar hendak menggugat gaya berfilsafat RG yang “genit,” penuh sensasi, Filsafat mengalami “malpraktek,” menjadi alat “propaganda,” “turun kelas,” dan sebagian menyamakannya dengan kaum “sofis” pada epos Yunani kuno. Pendek kata, RG dianggap telah menyelewengkan Filsafat dari makna awalnya karena mengkritik kekuasaan Presiden secara membabi-buta dan tak mengkritik—atau tak mau mengkritik—orang-orang/kelompok yang mengkritik pemerintah juncto Oposisi.
Barangkali kalau bukan Musim Pemilu, kritik RG terhadap pemerintah yang selalu menusuk ulu hati itu tak bakal membuat banyak orang “was-was.” Bahkan mungkin untuk sebagian, utamanya komunitas-komunitas Filsafat, kritik RG justru malah digandrungi, bukan hanya karena membuat kaum milenial melek politik dan Filsafat, tetapi lebih dari itu, justru karena masyarakat umum jadi lebih paham “apa itu Filsafat” sekaligus populer dengan istilah-istilah “filosofis.” Dengan begitu, Filsafat tidak hanya bisa dinikmati oleh “distinguish people” tetapi juga oleh orang-orang kebanyakan.
Namun karena Musim Pemilu, kritik RG yang belakangan pengaruhnya semakin melambung di udara—utamanya di kalangan milenials—membuat sebagian orang khawatir; ia bakal semakin sulit dikendalikan dan diisolasi, dan yang paling mengerikan, pengaruhnya bakal berdampak pada menurunnya elektabilitas Presiden dan calon Presiden. Untuk sebagian orang, sepak terjang RG bukan hanya mengkhawatirkan tetapi sekaligus membahayakan. Karena itu ikhtiar untuk mengendalikan dan mengisolasi kedigdayaan dan pengaruhnya harus segera dilakukan, setidaknya dengan, “katanya,” mengembalikan Filsafat pada habitatnya semula melalui para resi (skolar-skolar Filsafat) dengan tagar “#MenolakPembusukanFilsafat.”
Jalan Oposisi
Sejak dahulu kala posisi politik RG ditakdirkan berada di “jalan Oposisi.” Takdir ini sepertinya bukan suatu kebetulan, tapi lebih semacam penghayatan-diri tentang makna berfilsafat. RG sepertinya paham betul bahwa “sejarah Filsafat adalah sejarah Oposisi.” Apabila tidak ada Oposisi, sejarah filsafat mungkin juga tak bakal ada. Makanya ia menempuh jalan itu.
Jalan Oposisi RG bisa dilihat dengan menelusuri jejak-jejaknya di masa lalu. Bagi sebagian orang yang kenal “agak” dekat dengan RG, kritiknya yang tajam menusuk ulu hati sesungguhnya bukan barang kemarin sore. Ia telah malang melintang di dunia “kegetiran” itu sejak dahulu kala, sebelum pemerintahan demokratis di negeri ini dimulai. Bagi saya, justru kritikan RG hari kini sama tajamnya saat rezim SBY berkuasa, bahkan jauh sebelum rezim-rezim kemarin sore. Saat SBY berkuasa, misalnya, RG juga jarang atau bahkan tak pernah, mengkritik Oposisi—sebagaimana ia juga tak melakukannya hari-hari kini. Dengan posisi ini tak ada satu pun orang yang mempersoalkannya sebagaimana sekarang.
Pada zaman SBY, RG juga sering mengisi acara Tipi-Tipi, utamanya Tv Oposisi, untuk mengkritik kebijakan pemerintah dan seterusnya. Seperti biasa, ia juga sering mengisi seminar-seminar, dan saya pernah mengundangnya dalam diskusi publik tak kurang dari 2 kali pada 2009 lalu. Dalam diskusi-diskusi tersebut, letupan-letupan idenya masih sama dan sangat khas: penuh kejutan, diksi dan artikulasi publiknya memikat sekaligus memukau, dan tampak sangat genial.
Namun demikian, nama RG di era sebelumnya tak semelambung seperti pada era ini. Penanda itu, setidaknya bisa dilihat dari slogan yang kini melekat dengan dirinya di lini masa dan forum Tipi swasta yang bertajuk ILC: “No Rocky No Party.” Tak hanya itu, RG juga digandrungi kaum milenialsdi berbagai daerah, utamanya yang memiliki akses pada Tipi dan media sosial. RG seolah-olah menjadi magnet baru bagi kalangan melineals dari Sabang sampai Merauke. Bahkan, RG mengalahkan kepopuleran “Mukidi” yang sempat “ngehits” beberapa tahun belakangan.
Dalam amatan paling sederhana saya, setidaknya ada 2 hal yang membuat pengaruh RG meluas. Pertama, absennya kaum intelektual dan filsuf yang menempuh jalan Oposisi. Kalaupun ada 1-2 intelektual yang menempuh jalan ini, sikapnya masih malu-malu kucing, khawatir dicap tidak “Pancasilais,” satu baris dengan partai politik Oposisi, penyebar hoax, dan melawan kekuasaan yang sah. Karena itu, tak ada kritik yang nyaring dari kaum intelektual, yang ada hanya samar-samar. Sebagian besar kaum intelektual dan filsuf terserap ke dalam kekuasaan, kalaupun tidak , mereka mengambil posisi absen.
Sementara pada saat yang sama, dan ini yang kedua, rezim penguasa saat ini tidak begitu paham dasar-dasar mengatur negara, amburadul, meminjam istilahnya Prof Salim Said, “amatiran,” dan yang lebih parah lagi memainkan politik “Oposisi-Biner”: menempatkan warga negara yang tak setuju kebijakan pemerintah sebagai “lawan”—mereka bukan bagian dari kita—bahkan sebagian ada yang ditangkap. Dengan demikian, situasi politik menjadi keruh, becek, menjenuhkan, dan memperkuat kesan bahwa rezim ini anti kritik. Menggambarkan situasi ini, junior saya yang masih melineals mengatakan: “Presiden sudah kaya Nabi, kalau kita kritik, kita akan dihujat oleh para pengikutnya.”
Alhasil, tak ada kemeriahan dan kesemarakan berwarga negara, tak ada saling percaya antar warga negara, dan tak ada kohesi sosial di setiap lini pergaulan. Ruang-ruang publik penuh caci maki, di media sosial, forum-forum diskusi, talkshow Tv-Tv, dan seterusnya. Di tengah situasi politik yang involutif inilah, RG tetap berdiri tegap, menabuh genderang perang dengan suara lantang mengkritik pemerintah dengan kritikan yang tajam, logis, penuh metafor, dan pilihan diksinya memesona. Keberanian RG yang konsisten mengambil posisi politik jalan Oposisi, justru menuai panen yang melimpah. Pelan tapi pasti, banyak warga negara—khususnya kaum melineals—tiba-tiba mendapatkan juru bicara baru yang “tepat” di ruang-ruang publik menghadapi kekuasan.
Tak heran, dalam waktu yang relatif singkat, nama RG kian melambung tinggi di udara, digandrungi hampir oleh semua kalangan, mulai dari bapak-bapak, emak-emak sampai kaum melineals. Pernyataan-pernyataan politiknya di media sosial paling dicari dan tak kurang dari 4 juta orang telah menontonnya di channel youtube. Tak hanya itu, ia diundang di banyak tempat dan lembaga untuk memberikan kuliah, menyampaikan pencerahan politik kepada ummat dari semua kalangan. Kehadirannya dielu-elukan, dan semakin hari, kaum melineals semakin banyak yang menjadi fans beratnya.
Apabila situasi ini terus berlanjut, maka pertanda tidak menguntungkan bagi Presiden yang juga calon Presiden; elektabilitasnya terancam, karena sebagaimana dikatakan di awal, RG menempuh jalan Oposisi yang tentu menguntungkan bagi calon Presiden dan partai-partai Oposisi.
Mengancam Elektabilitas
Dalam situasi yang demikian, tiba-tiba secara bergelombang para figur ternama ramai-ramai menggugat posisi politik RG. Tak kurang dari artikel-artikel pendek dan rilis media disebarkan, diskusi-diskusi Filsafat diselenggarakan. Apakah itu semua kebetulan atau disengaja? Entahlah . . .! Dilihat dari perspektif yang paling canggih sekalipun, gelombang kritik tersebut tak bisa lari dari sebuah bentuk kekhawatiran terhadap ancaman elektabilitas calon Presiden daripada penolakan terhadap pembusukan Filsafat. Untuk membuktikan tesis yang terakhir ini, marilah kita urai satu per satu.
Jika diperas, gelombang kritik yang ditujukan kepada RG secara garis besar bisa digambarkan sebagai berikut: ia tak mengkritik—atau tak mau mengkritik—Oposisi dan hanya mau mengkritik Presiden. Posisi itu membuat dirinya dianggap tidak “netral” karena condong pada Paslon 02 sebagai Oposisi. RG dianggap mereduksi makna akal sehat karena hanya mau mengkritik Presiden dan tidak yang lain, anggota parlemen misalnya—sebagai kepanjangan Oposisi di DPR; RG sedianya membela “kebenaran” karena kebenaran tetaplah kebenaran entah itu ada di Presiden ataupun Oposisi; bahkan ia dianggap mengidap “akal sakit”—lawan dari akal sehat yang menjadi icon dirinya—karena kritiknya lebih berbentuk “ressentiment”, suatu tipe mentalitas budak menurut Nietzsche, sebagai sublimasi atas ketakberdayaan dirinya melawan kekuasaan.
Para pengkritik RG tak memahami RG secara “utuh,” dan juga tak memahami secara baik bagaimana anatomi “kekuasaan” beroperasi di negeri ini. Mungkin karena pengaruh Musim Pemilu sehingga cara pandang mereka menjadi one dimensional man: RG anti Presiden juncto Paslon 01. Titik. Dalam pengetahuan singkat saya, dalam banyak kesempatan RG tak hanya mengkritik Presiden tetapi DPR juga kena palu godamnya. Kritik keras terhadap UU MD3, UU Pemilu dan UUD lainnya selalu ia ulang-ulang di banyak kesempatan sebagai produk “abal-abal,” jika tak ingin dikatakan buruk sekali. Tetapi sayangnya kritikan itu tak diperhatikan oleh pengkritik RG sehingga seolah-olah tak cukup untuk menempatkan RG sebagai pengkritik semua bentuk kekuasan yang sewenang-wenang. Sekali lagi, mungkin ini karena pengaruh Musim Pemilu yang lebih fokus pada pro 01 atau anti 01. Yang diperhatikan dari RG hanya yang anti-01 bukan yang lainnya.
Berikutnya, kebenaran ada di mana-mana entah di Presiden atau Oposisi; demikian juga kesalahan, ada di mana-mana entah di Oposisi atau Presiden. Kenapa hanya mengkritik Presiden, Oposisi tak dikritik? Pertanyaan ini memperlihatkan bahwa para pengkritik RG tidak paham bagaimana kekuasaan Istana beroperasi secara mematikan. Gejala umum yang terjadi pasca Presiden Gus Dur, ketika seseorang dilantik menjadi Presiden, semua kekuatan “kekuasaan” di luar dirinya berusaha untuk disedot ke dalam Istana. Bukan hanya lembaga-lembaga yang berada di bawahnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian; juga lembaga-lembaga yang setara seperti peradilan dan DPR-MPR; tetapi kekuasaan Oposisi pun dipreteli satu persatu kedigdayaannya hingga menjadi “macan ompong” pesakitan. Dengan keberadaan partai politik yang begitu fragmented, partai Oposisi ibarat “Binatang jalang, dari kumpulannya terbuang,” karena partai-partai pendukung Oposisi yang tidak inti ramai-ramai menghamba pada kekuasan.
Di tengah situasi politik yang demikian, kita ajukan pertanyaan sederhana: adakah yang lebih pantas dan layak dikritik selain daripada kekuasaan mutlak Presiden? Dalam situasi yang demikian pula, apakah Oposisi lebih layak dikritik dibandingkan Presiden? Jika mengkritik Oposisi dianggap lebih layak, kita ajukan pertanyaan lanjutan: lalu siapa yang mengurusi hajat hidup semua warga negara dari Sabang sampai Merauke: Oposisikah atau Presidenkah? Presiden atau Oposisi yang potensial melakukan penyimpangan dalam mengurus hidup hajat orang banyak, termasuk KKN? Dalam pokok ini sepertinya saya tak perlu terlalu serius dan capek-capek mengajari figur-figur ternama yang mengkritik posisi politik RG itu. Mereka lebih paham jawabannya daripada saya karena semuanya adalah skolar-skolar lulusan luar negeri serta pakar-pakar filsafat yang memiliki teori canggih. Ini tak lebih sekedar soal ancaman elektabilitas Presiden saja sehingga mereka sangat berkepentingan untuk menghentikan atau minimal memperlambat laju pengaruh RG di kalangan akar rumput dengan, salah satunya, mengkritik posisi RG.
Pokok yang lain, kritik RG dianggap tak lebih sekedar “ressentiment”, suatu tipe mentalitas budak menurut Nietzsche, sebagai sublimasi atas ketakberdayaan dirinya melawan kekuasaan. Namun jika kita setia dengan Nietzsche, dan menganggap kritik RG adalah buruk, sekedar ressentiment, maka kita tak akan memperdulikan kritik-kritik RG, apalagi meresponnya. Karena secara gamblang Nietzsche mengatakan dalam salah satu bukunya, yang saya kutip secara bebas di sini, *“Kepada hal-hal buruk, kita harus palingkan muka.”* Jika kita menganggap kritik RG adalah buruk, seharusnya kita palingkan muka. Tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Kritik RG justru menuai respon secara sengaja dari barisan figur-figur ternama. Ini membuktikan bahwa kritikannya RG terhadap Presiden bukan karena tidak objektif atau buruk, tetapi lebih sekedar ancaman terhadap elektabilitas Presiden dan calon Presiden. Beginilah memang di setiap Musim Pemilu!
Sebagai penutup, jk RG dianggap sebagai kaum sofis, sepertinya itu masih relatif “mendingan” karena ia berada di seberang kekuasaan. Yang lebih “menggelikan” lagi adalah kaum sofis yang berada di bawah “ketiak” dan “tangan-tangan” kekuasan, yang secara tiba-tiba ingin menjadi Dewi Pengadil bahwa RG telah membusukkan filsafat.
Ah . . . saya tiba-tiba baru sadar! Ternyata ini bukan soal pembusukan Filsafat, tetapi soal *Ketika Filsafat Mengancam Elektabilitas.*
*Oleh Liban M. Hayinas, Alumnus Pondok Pesantren Annuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep, Madura.